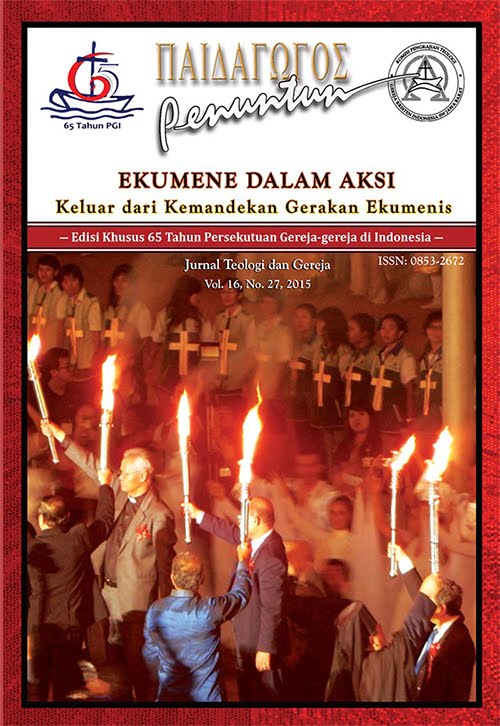(Catatan Diskusi KPT GKI SW Jabar mengenai
Kebijakan
Agraria Yusuf di Mesir)
 Kitab Kejadian 47:13-26, diberi judul “Tindakan Yusuf”
oleh Lembaga ALkitab Indonesia (LAI), memuat cerita mengenai kebijakan yang
diambil Yusuf di tengah bencana kelaparan yang melanda wilayah Mesir dan
Kanaan. Bagian ini (Kej. 47:13-26) dibuka dengan cerita mengenai bagaimana
Yusuf mengumpulkan uang dari hasil penjualan gandum dan membawanya ke dalam
Istana Firaun (Kej. 47:13-14). Kemudian, ditutup dengan sebuah ketetapan yang
berhubungan dengan kebijakan agrarian di Mesir: “Yusuf membuat hal itu menjadi
suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa seperlima
dari hasilnya menjadi milik Firaun; hanya tanah para imam yang tidak menjadi
milik Firaun” (Kej. 47:26).
Kitab Kejadian 47:13-26, diberi judul “Tindakan Yusuf”
oleh Lembaga ALkitab Indonesia (LAI), memuat cerita mengenai kebijakan yang
diambil Yusuf di tengah bencana kelaparan yang melanda wilayah Mesir dan
Kanaan. Bagian ini (Kej. 47:13-26) dibuka dengan cerita mengenai bagaimana
Yusuf mengumpulkan uang dari hasil penjualan gandum dan membawanya ke dalam
Istana Firaun (Kej. 47:13-14). Kemudian, ditutup dengan sebuah ketetapan yang
berhubungan dengan kebijakan agrarian di Mesir: “Yusuf membuat hal itu menjadi
suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa seperlima
dari hasilnya menjadi milik Firaun; hanya tanah para imam yang tidak menjadi
milik Firaun” (Kej. 47:26).
Di antara bagian
pembuka dan penutup, terdapat dua proposal yang mewarnai dialog antara Yusuf
dengan penduduk Mesir terkait bencana kelaparan. Proposal pertama diusulkan
oleh Yusuf, yakni barter antara ternak (kuda, kambing domba,lembu sapi dan
keledainya) yang dimiliki rakyat Mesir dengan makanan yang disediakan oleh
pihak kerajaan (Kej. 47: 15-17). Sementara proposal kedua – setelah uang dan
ternak mereka (rakyat Mesir) habis – datang dari rakyat Mesir, yakni pihak
kerajaan bukan saja membeli tanah, tapi juga membeli rakyat mesir dan
menjadikan mereka hamba (budak). Setelah itu, pihak kerajaan memberikan makanan
dan benih yang harus ditaburkan (digarap) di tanah yang sudah dikuasai pihak
kerajaan. Kesepakatan ini kemudian diikuti ketentuan bagi hasil panen yang
ditentukan oleh Yusuf (kerajaan): “Mengenai hasilnya, kamu harus berikan
seperlima bagian kepada Firaun, dan yang empat bagian lagi, itulah menjadi
benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu,
dan menjadi makanan anak-anakmu" (Kej. 47: 24).
Dalam penelusuran Yonky Karman (dosen Perjanjian Lama
dari STT Jakarta yang menjadi pembicara), teks ini (Kej. 47: 13-26) telah lama
menjadi perdebatan di kalangan akademisi mengingat Yusuf dipandang
mempraktekkan perbudakan yang justru bertentangan dengan semangat pembebasan dalam kitab keluaran. Bahkan, narasi ini tidak memperlihatkan
Yusuf sebagai seorang yang berakal budi dan bijaksana.
Asal-usul Teks
Dalam memahami Kej. 47: 13-26, karman mengajak kita
melihat keberadaan narasi tersebut sebagai sebuah blok yang diletakkan (disisipkan)
antara Kej. 47: 11-12 dan Kej. 47: 27-28. Apabila blok narasi tersebut (Kej. 47:
13-26) dikeluarkan maka alur cerita pada dua bagian kitab Kejadian (Kej. 47:
11-12 dan Kej. 47: 27-28) akan terihat mengalir. Karman kemudian menyimpulkan
bahwa blok narasi ini sesungguhnya berdiri sendiri, namun kemudian disisipkan
ke dalam kisah para leluhur Israel. Apabila demikian, lalu bagaimana sebenarnya
asal-usul dari blok ini?
Dalam uraian yang disampaikan oleh Karman, asal-usul dari
Kej. 47: 13-26 tampaknya sulit untuk ditemukan. Karman memperkirakan blok ini
terkait dengan situasi politik yang terjadi di kerajaan Utara (Israel)
mengingat: (a) istilah bet yosep
(keturunan Yusuf) umumnya merujuk penduduk di kerajaan Utara (Am. 5:6, 15; 6:6;
Ob. 18; Za. 10:6), sementara bet Yehuda
(kaum Yehuda) untuk kerajaan Selatan, (b) munculnya unsur-unsur Mesir di dalam
blok tersebut. Oleh karena itu, menurut Karman, kemungkinan blok ini digunakan
oleh kerajaan Utara – yang saat itu (pasca Salomo) mendapat dukungan dari
kerajaan Mesir – terkait kebutuhan akan legitimasi politik atas wilayah Utara
dan Selatan. Dalam blok narasi tersebut, Yusuf bukan saja mendapat dukungan
dari Firaun, namun juga dijadikan berkuasa atas seluruh wilayah Mesir. Alur ini
terlihat mirip dengan posisi Yerobeam I (raja pertama di wilayah Utara; ± 930 –
909) yang saat itu mendapat dukungan politik dari Sisak (raja Mesir yang
memberi perlindungan bagi Yerobeam I saat Salomo masih berkuasa).
 Kesulitan di atas, terkait asal-usul blok narasi Kej. 47:
13-26, membawa Karman pada pemikiran bahwa penelusuran terhadap fungsi dan
makna dari narasi tersebut jauh lebih penting. Dengan kata lain, apabila blok
narasi Kej. 47: 13-26 adalah sebuah sisipan yang asal-usulnya sulit ditentukan, lalu apa fungsi dan
makna sisipan tersebut dalam kisah leluhur Israel?
Kesulitan di atas, terkait asal-usul blok narasi Kej. 47:
13-26, membawa Karman pada pemikiran bahwa penelusuran terhadap fungsi dan
makna dari narasi tersebut jauh lebih penting. Dengan kata lain, apabila blok
narasi Kej. 47: 13-26 adalah sebuah sisipan yang asal-usulnya sulit ditentukan, lalu apa fungsi dan
makna sisipan tersebut dalam kisah leluhur Israel?
Fungsi Narasi
Dalam rangka menelusuri fungsi dari blok narasi
Kej. 47: 13-26, Karman meletakkannya dalam konteks sejarah
leluhur Israel dan kisah eksodus, serta memperhatkan informasi/keterangan
penting yang hendak ditonjolkan dalam narasi tersbut. Hal ini kemudian membawa Karman pada pemikiran bahwa, pertama,
blok ini berperan untuk menghubungkan tradisi mengenai leluhur Israel (Kej.
12-50) dengan tradisi eksodus (Kel. 1-12). Khususnya, terkait migrasi keturunan
Yakub di Mesir dan kekejaman yang terjadi setelah Yusuf yang menjadi pemicu peristiwa
eksodus. Kedua, blok narasi ini juga memiliki fungsi etiologi, yakni
menjelaskan: (a) penguasaan tanah rakyat oleh pihak kerajaan, (b) pungutan
(upeti) seperlima dari hasil panen untuk kerajaan dan (c) tidak diambilnya
tanah para imam oleh pihak kerajaan. Menurut Karman, biasanya fungsi etiologis
dimasukan karena narrator ingin menjelaskan asal-usul dari sebuah peristiwa
atau praktik tertentu yang sudah
tidak diketahui lagi oleh audiens pada saat narasi tersebut ditulis. Lalu
fungsi ketiga, Karman memperkirakan blok narasi ini berperan juga untuk
menjelaskan perbedaan penguasaan tanah yang terjadi di Mesir dan Israel.
Berdasarkan alur dalam blok narasi tersebut, penguasaan
tanah rakyat oleh pihak kerajaan terjadi pada: (a) masa kelaparan, (b) atas
proposal dari rakyat Mesir sendiri dan (c) peran Yusuf yang menonjol dalam
politik agraria, termasuk penetapan pungutan (upeti) atas tanah. Alur seperti
ini memperlihatkan peran Yusuf yang sangat penting dalam penguasaan tanah
rakyat oleh pihak kerajaan dan penetapan upeti. Apabila diletakan secara
historis, Karman memandang tidak ada data historis yang menunjukan bahwa Yusuf
merupakan biang keladi penguasaan tanah rakyat oleh kerajaan. Kisah Yusuf
biasanya diletakkan pada masa Hiksos (± 1803-1550 SM.), sementara penguasaan
tanah oleh kerajaan baru terjadi setelah masa Hiksos (± 1540-1070 SM.). Ini
belum lagi posisi raja Mesir yang dipandang sebagai titisan dewa sehingga
secara otomatis berkuasa atas tanah di seluruh wilayah kerajaan. Hal ini
membuat Karman memandang bahwa blok narasi mengenai tindakan Yusuf (Kej. 47:
13-26) merupakan midras etiologis yang berada di luar kerangka kisah Yusuf dan
berfungsi menjelaskan beberapa hal di atas.
Teks dan Masalah Perbudakan
Persoalan yang sangat sensitif terkait blok narasi Kej.
47: 13-26 adalah praktik perbudakan di mana
Yusuf berperan di dalamnya. Memang,
sebagaimana terlihat pada teks, rakyat Mesirlah yang mengusulkan agar Yusuf
(pihak kerajaan) membeli mereka (rakyat) dan tanah mereka mengingat
beratnya bencana kelaparan saat itu. Namun, Yusuf pada dasarnya melaksanakan kebijakan istana yang
bukan saja mengambil alih ternak yang dimiliki rakyat, tetapi juga tanah dan
rakyat itu sendiri. Dengan kata lain, bencana kelaparan dimanfaatkan oleh Yusuf
(pihak kerajaan) untuk menguasai seluruh alat produksi, termasuk menguasai rakyat
itu sendiri.
Pada ayat 21, digambarkan bahwa setelah Yusuf mengambil
alih semua alat produksi maka rakyat mulai diperhambakan (budak) oleh pihak
kerajaan: “Dan tentang rakyat itu, diperhambakannyalah mereka di daerah Mesir
dari ujung yang satu sampai ujung yang lain” (Kej. 47:21). Menurut Karman,
dalam kitab suci Yahudi (JPSV dan TNK) tidak digunakan istilah “diperhambakan”,
melainkan “memindahkan”.
And as for the people, he removed them city by city, from
one end of the border of Egypt even to the other end thereof (JPSV, 1917).
And he removed the
population town by town, from one end of Egypt’s border to other (TNK, 1985).
Ini berbeda dengan Septuaginta (LXX) dan Pentateukh
Samaria yang menggunakan istilah “memperhambakan”, bukan “memindahkan”. Menurut Karman, perbedaan ini bisa terjadi pada saat penyalinan kitab suci mengingat kata h’byr (memindahkan) dan h’byd (memperhambakan) memuat di dalamnya
bentuk huruf yang mirip, yakni huruf “R” (ר) dan huruf “D” (ד). Para penafsir umumnya memilih
istilah “memperhambakan”, sebagaimana digunakan dalam Septuaginta (LXX) dan
Pentateukh, karena memindahkan seluruh penduduk dari kota ke kota dipandang tidak
rasional; sulit dilakukan. Terlepas dari istilah mana yang hendak digunakan,
Karman berpendapat bahwa realitas yang ditemukan di dalam teks adalah pihak kerajaan menjadi
pemilik (penguasa) atas tanah dan atas rakyat, sementara rakyat hanya bekerja
sebagai penggarap. Kemudian, seperlima dari hasil panen harus diberikan kepada
pihak kerajaan sebagai upeti karena mereka (rakyat) mengelola tanah kerajaan.
Selain masalah penyalinan, persoalan juga ditemuka pada penerjemahan
istilah ébed dalam konteks idiom
(konstruksi kalimat): haya + ébed + preposisi lĕ + persona. Dalam
konstruksi ini, istilah ébed kadang
diterjemahkan menjadi ‘hamba’ (Kej. 9:26) , ‘budak’ (Kej. 44:10), ‘takluk’
(2Raj. 17:3), ‘melayani’ (Ams. 11:29; Alkitab BIS) dan ‘bekerja’ (Ams. 12:9).
Terkait masalah ini, Karman mengusulkan agar istilah ébed dalam blok narasi Kej. 47: 13-26 diterjemahkan dengan mengacu
pada Ams. 11: 29 dan 12: 9 sehingga terjemahannya menjadi “kami dengan tanah
kami akan melayani Firaun (ay. 19) dan “kami akan bekerja untuk Firaun” (ay.
25).
Berdasarkan apa yang ada pada teks di atas, sesungguhnya perbudakan
tidak terlihat sebagai praktik penindasan dan kekejaman dari pihak Yusuf (kerajaan) terhadap rakyat. Bahkan,
bagi hasil (upeti) yang ditetapkan Yusuf (kerajaan) hanya sebesar seperlima (20%)
dari hasil panen. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan upeti yang
berlangsung pada masa Hammurabi, yakni berkisar 50%-66%. Selain itu, menurut
Karman: (a) dalam blok narasi Kej. 47: 13-26 tidak muncul perlawanan atau
keluh kesah rakyat terhadap kebijakan agrarian yang dilakukan pihak kerajaan, dan (b) tidak ada catatan sejarah yang memperlihatkan perlawanan rakyat terhadap praktik perbudakan. Sebaliknya,
dalam konteks bencana kelaparan, rakyat Mesir
menyetujui dan
berterima kasih atas kebijakan agrarian tersebut: “Lalu berkatalah mereka:
"Engkau telah memelihara hidup kami; asal kiranya kami mendapat kasih
tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun” (ay. 25). Oleh karena itu, bagi
Karman, praktik perbudakan (hamba) yang berlangsung dalam blok narasi ini harus
dibaca dalam konteks standar moral Timur Tengah kuno. Dengan kata lain, praktik
yang ada dalam blok narasi Kej. 47: 13-26 tidak bisa diidentikan dengan isu empire di mana kekuatan modal (the power of capital) menerjemahkan diri
ke dalam struktur kerakusan yang menindas dan menghisap segala aspek dalam
kehidupan manusia.
Penutup
Dalam refleksinya, Karman memandang bahwa blok narasi Kej.
47: 13-26 tetap relevan dibaca dalam konteks politik pangan dunia ketiga
mengingat negara hadir untuk memastikan ketersediaan dan kemandirian pangan
bagi rakyatnya. Memang, dalam narasi ini negara tampil begitu kuat sehingga muncul
bentuk kapitalisme negara dalam
dunia Timur Tengah kuno. Namun, bagi
Karman, masalah ini tetap harus dilihat baik dalam konteks Timur Tengah Kuno
maupun peran yang kuat dari negara untuk mengupayakan kemandirian pangan.